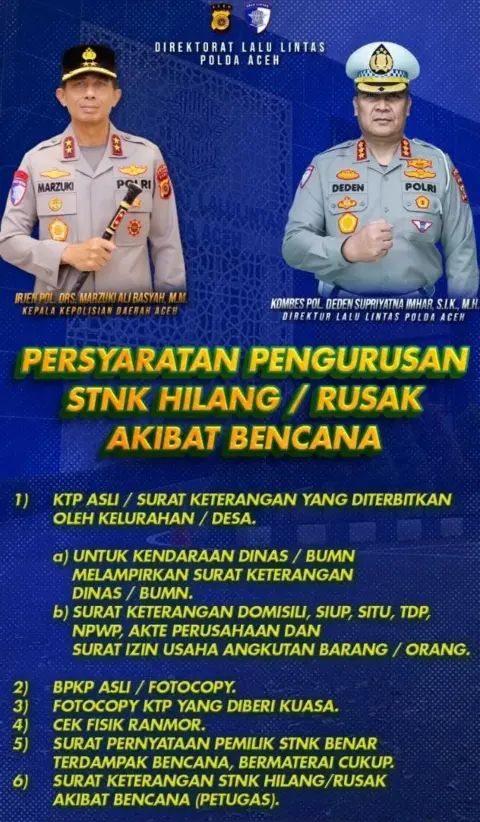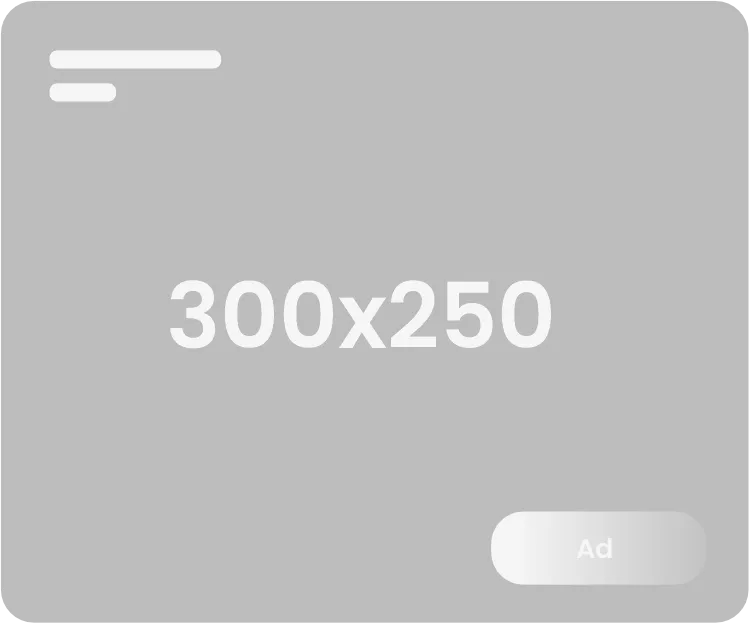ACEH SELATAN | REALITAACEH – Di dunia yang setiap detiknya dibanjiri informasi, kebenaran semakin kehilangan rumahnya. Kalimat-kalimat lahir dari jemari yang tergesa, berita disusun bukan dari nurani, melainkan dari kalkulasi, siapa yang diuntungkan, siapa yang tersingkir. Dalam pusaran itu, profesi wartawan yang dulu disebut sebagai “penjaga akal sehat bangsa”, justru kini sering berada di titik paling rentan.
Kita hidup di zaman ketika gelar dan sertifikat menjadi penentu status sosial. Dalam dunia pers, sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sering dijadikan simbol bahwa seseorang telah “resmi” menjadi pewarta. Tapi sertifikat hanyalah kertas. Ia membuktikan seseorang pernah diuji secara teknis, namun tak menjamin bahwa hatinya diuji oleh nurani.
Rocky Gerung pernah berkata bahwa ijazah hanya menandakan seseorang pernah sekolah, bukan bukti bahwa ia pernah berpikir. Begitu pula jurnalis, menulis bukan berarti memahami, dan lulus uji kompetensi bukan berarti berani berkata benar.
Ketika Jurnalisme Kehilangan Jiwa
Menjadi wartawan bukan sekadar menyusun fakta, tapi merawat akal sehat publik. Namun, di banyak tempat, termasuk di Aceh Selatan, profesi ini perlahan kehilangan jiwanya. Ia terjebak dalam pusaran kepentingan, kekuasaan, dan keakraban semu dengan pejabat.
Tak sedikit yang kini lebih sibuk mencari kedekatan dengan bupati, kepala dinas, atau pengusaha. Pena tak lagi diarahkan untuk membela kebenaran, melainkan untuk memoles citra atau menjatuhkan rekan sendiri. Jurnalisme berubah menjadi transaksi yaitu antara ruang iklan, dukungan politik, dan ambisi pribadi.
Yang lebih menyedihkan, ada wartawan yang ketika kalah dalam gelanggang politik, justru kembali merapat ke kekuasaan baru yakni menulis demi kenyamanan, bukan demi kebenaran. Padahal, bupati tidak butuh wartawan penjilat. Ia butuh suara jernih yang berani mengingatkan, bukan tangan yang sibuk menulis pujian.
Di Aceh, di mana adat dan syariat bersatu dalam kalimat adat ngon syara, lagee zat ngon sifeut, nilai dan tanggung jawab seharusnya tak bisa dipisahkan. Pena seorang wartawan Aceh mestinya berakar pada nilai itu, menulis dengan hati, bukan dengan kepentingan.
Antara Kuasa dan Nurani
Setiap wartawan membawa beban moral yang tak ringan yaitu menjaga kebenaran di tengah kebohongan yang sistematis. Tapi banyak yang kini menyerah pada pragmatisme. Jurnalisme kehilangan daya gigitnya karena sebagian pelakunya rela dipelihara oleh kekuasaan.
Padahal, sejak lama, sejarah Aceh mengajarkan bahwa keberanian moral lebih berharga daripada kedekatan politik. Dari Cut Nyak Dhien hingga Teungku Chik di Tiro, keberanian bersuara selalu lahir dari keyakinan, bukan keuntungan. Jika semangat itu hilang dari dunia pers, maka sesungguhnya yang mati bukan sekadar profesi, tapi nurani kolektif masyarakat.
Walter Lippmann pernah menulis bahwa tugas utama jurnalis adalah menjadi “penyaring realitas” bukan memperbanyak suara, tapi memurnikan makna. Artinya, wartawan bukan sekadar penyampai pesan, tapi penjaga moral publik. Ia harus menimbang sebelum menulis, merenung sebelum mengabarkan, dan bertanggung jawab atas setiap kata yang disebarkannya.
Namun kini, di banyak ruang redaksi lokal, idealisme sering dianggap kemewahan. Wartawan yang kritis dicap berseberangan, yang independen dianggap tidak loyal, dan yang jujur malah dihindari. Padahal tanpa jurnalisme yang berani, pemerintah pun akan berjalan tanpa kontrol, dan rakyat kehilangan cermin untuk melihat kekuasaan.
Kembali ke Akar Kebenaran
Menulis berita seharusnya bukan tentang siapa yang disukai, tapi tentang apa yang benar. Pena bukan alat mencari muka, tapi sarana mengoreksi dan mencerdaskan. Jika tulisan tak lagi lahir dari nurani, maka setiap kalimat hanyalah suara kosong yang menipu diri sendiri.
Sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling banyak berita, tapi siapa yang paling setia pada kebenaran. Di tengah dunia yang penuh manipulasi dan kepalsuan, tugas wartawan bukan memperindah wajah kekuasaan, tapi menjaga wajah kebenaran agar tak pudar.
Mungkin kini saatnya setiap pewarta kembali bercermin, untuk siapa pena ini bekerja? Untuk kebenaran, atau untuk kenyamanan pribadi?
Karena pada akhirnya, ketika tinta kering dan berita usang, yang tersisa hanyalah satu hal yaitu nama baik yang ditulis oleh nurani.
Oleh: Bang Iwan (Hanzirwansyah)
Pemerhati Sosial dan Komunikasi Publik